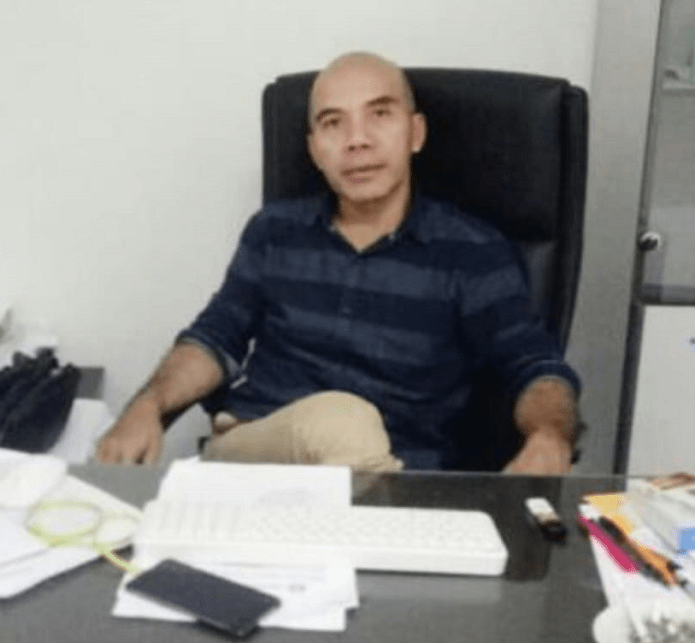[ad_1]
Oleh: Sumadi Dilla (Dosen Komunikasi dan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Halu Oleo)
Tulisan ini tidak bermaksud menuduh dan menghakimi pendapat dan sikap politik seseorang dalam pemilihan presiden saat ini. Perbedaan pandangan, sikap dan tindakan politik yang terjadi adalah pilihan asasi masing-masing. Karenanya, kehadiran tulisan ini sekedar memperkaya perspektif bacaan politik semata.
Memasuki tahun pemilu 2024, iklim perpolitikan tanah air semakin semarak. Pasca penetapan pasangan calon Presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, tiga (3) pasangan calon presiden dan wakilnya, sibuk dan intens menyusun pesan dan agenda politik yang akan tawarkan ke publik. Seiring dengan itu, masing-masing calon presiden/wakil presiden, bersama partai politik pengusungnya membangun narasi, diksi, slogan, ungkapan dan simbol simbol kampanye mereka.
Upaya itu dilakukan dalam rangka meraih dukungan seluruh rakyat (pemilih) Indonesia. Jika kita jeli dan kritis mengamatinya, sekumpulan strategi dan pesan politik tersebut, ada yang relevan, logis dan dibutuhkan. Namun terdapat pula beberapa hal yang perlu disangsikan korelasinya dengan kebutuhan warga negara dan kondisi masyarakat saat ini. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia hal itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa. Namun terlepas dari kewajaran dan kebiasaan tersebut, terdapat sesuatu yang perlu kita cermati dengan nalar kesadaran rasional kita.
Pergeseran Tema dan Narasi
Di tengah hingar bingar dan gencarnya arus pesan politik tiga kontestan calon presiden saat ini, terdapat suatu kesamaan dan kemiripan narasi yang pernah terjadi pada pilpres 2014 dan 2019. Kesamaan atau kemiripan tersebut diusung oleh salah satu pasangan calon presiden yang notabene kerabat sang number one. Pergeseran dimaksud berkaitan dengan tema dan narasi kerakyatan serta kebangsaan menjadi mitos-mitos politik.
Hal ini dapat terlihat dari: (1) hilangnya tema kerakyatan yang konkrit dan solutif; (2) beralihnya keunggulan gagasan menjadi narasi mitos kemewahan sosok figur calon presiden dan wakilnya. Sejatinya seluruh agenda dan pesan politik calon presiden berbasis gagasan masalah kerakyatan dan kebangsaan yang real, penting dan urgen.
Gagasan dan program yang mesti dilakukan sangat minim ditonjolkan dan tidak begitu jelas diuraikan. Orientasi dan fokus narasi yg dibangun hanya bersifat gimik politik yang bersifat sentralistik personal, cenderung manipulatif. Bahkan dari apa yang ditunjukkan dalam kampanye mereka dan debat capres di KPU RI, terdapat pasangan calon presiden yang justru mengumbar harapan belaka.
Seluruh bangunan narasi bertumpu pada bayang-bayang prestasi dan kekuatan pesona sang figur, ibarat sebuah mitos yang sulit dibuktikan. Eksploitasi terhadap mitos-mitos tersebut sebagai pesan politik sengat masif ditanamkan ke benak publik pemilih. Jika dahulu misalnya, mitos pemilihan presiden diproduksi secara malu-malu oleh partai politik pengusung bersama dengan calon presiden.
Sedangkan pada pemilihan presiden 2024, produktivitas mitos secara vulgar, telah mengalami pabrikasi secara masif, dikendalikan oleh kekuatan dan figur ‘orang besar’ yang notabene berhubungan dengan rezim pemerintah (penguasa), dengan sedikit campur tangan calon presidennya. Sampai disini kita dapat mengatakan bahwa mitos telah menjadi dan menjelma sebagai instrumen utama sekaligus tujuan berpolitik dan berdemokrasi dalam meraih dukungan dan partisipasi pemilih. Sebagai instrumen dan tujuan politik, mitos dipergunakan sebagai sihir ajaib dalam mengeksplorasi, mengeksploitasi dan mengkooptasi dunia rasional publik.
Mitos Politik dan Irasional Pemilih
Sebagai produk mitos politik, daya magis mitos tersebut diharapkan menciptakan sensasi imaginer pada diri individu menjadi pribadi pemilih yang irasional. Pemilih dalam kategori ini mendasarkan partisipasi politiknya pada pilihan-pilihan pragmatis. Kecenderungan tindakan politik mereka searah, seragam, serempak, super loyalis dan bersifat hayali.
Jika demikian faktanya, kita bisa merenungkan dan membayangkan, bahwa pemilihan presiden 2014, 2019 dan 2024 nanti, telah dan akan diramaikan pemilih yang bertindak diluar logika rasional. Ibarat pemilih semu yang dituntun oleh kekuatan mistik dari mitos, diluar kesadaran dan akal sehatnya. Dengan kondisi seperti itu, tidak berlebihan juga kita mengatakan bahwa apa yang telah dan sedang terjadi di negeri ini, tidak sedang baik- baik saja.
Hasil pemilihan presiden 2014 dan 2019 misalnya, terdapat beberapa program dan agenda politik belum tercapai dan tidak terbukti. Kondisi sosial, budaya’ ekonomi, politik dan hukum mengalami pasang surut sebagai buah dari sihir mitos pilpres. Alhasil, mitos pada pilpres kontra produktif dengan kenyataan, sebagaimana tesis Barthes,R, (Hoed,B; 2014) bahwa mitos sebagai pesan (politik)
dapat diyakini kebenarannya tetapi tidak dapat dibuktikan. Bahkan Bastian dan Mitchell (2019), mempertegasnya bahwa mitos akan berfungsi positif jika berkaitan hal primer (kepercayaan, tradisi, adat) dalam sistem sosial budaya. Sebaliknya akan bersifat negatif terhadap hal-hal sekunder (ide, pikiran, tindakan) karena di luar logika.
Sehingga membincangkan dan menyandingkan mitos sebagai narasi, pikiran dan tindakan dalam praktik politik adalah penting untuk diketahui. Demikian juga membongkar praktik mitos dalam isi pesan dan agenda politik calon presiden, jauh lebih perlu. Jika menggunakan tradisi semiotika maka mitos dalam politik muncul sebagai produk budaya politik tradisional. Karenanya, mitos difungsikan khusus untuk menjelaskan sesuatu yang belum mampu disentuh logos, atau nalar akal, sebagaimana kata Karen Armstrong. Bahkan menurut Armstrong seleksi waktu menyebabkan mitos hadir dalam berbagai bentuk, ruang sosial dan interaksi masyarakat sehingga terkomodifikasi sebagai komoditas untuk berbagai jenis tujuan (Endibiaro, 2014).
Dengan mengikuti pandangan Amstrong, maka mitos, akan selalu hadir, eksis, dan menonjol dan memiliki tujuan tertentu dalam setiap momen perhelatan politik, termasuk pilpres 2024. Karenanya, tak heran pada pemilihan presiden 2024, praktek mitos baik pada pesan, agenda maupun kampanye politik patut dicurigai dan diwaspadai. Dengan perkataan lain, mitos digunakan untuk menutupi kelemahan, kekurangan atau ketidakmampuan mengelola dan menyelesaikan persoalan bangsa yang kompleks. Bahkan dengan cara seperti itu, bisa jadi calon presiden bersama kekuatan besar, (oligarki, partai politik, rezim) sedang melumpuhkan logika, nalar dan akal sehat kita dalam mengkritisi problematika bangsa.
Publik dipaksa, dijauhkan, dibelokkan, bahkan dikanalisasi dari diskursus publik dan partisipasi politik secara substantif. Menurut pandangan mereka, proposisi tentang masa depan bangsa (kepemimpinan, kesejahteraan) yang dianggap benar atau salah saat ini, hanya bisa benar atau salah jika kejadian masa depan ditentukan mereka. Realitas (politik) yang ada saat ini, tidak lepas dari campur tangan mereka sebagai bentukan dan kemasan yang bersifat manipulatif. Hal inilah yang disebut para ahli filsafat politik sebagai era fatalis politik dalam sebuah rezim kekuasan.
Fakta yang terjadi, narasi mitos dalam kampanye calon presiden, terlihat jelas diproduksi dan dikonstruksi secara sepihak (versi elit) sebagai realitas politik. Sadar atau tidak, dengan kondisi seperti itu mengakibatkan tersumbatnya diskursus publik. Pun, agenda publik dan partisipasi publik dalam merumuskan dan menyelesaikan persoalan kesejahteraan serta masa depan bangsa dinihilkan. Sebaliknya, mereka sibuk memoles kemewahan status, fasiltas, dan asal usul yang melekat pada figur calon presidennya semata.
Fenomena pergeseran gagasan menjadi mitos citra figur, telah dimulai dan dapat ditelusuri pada pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019. Pada pemilihan presiden saat itu, terdapat 3 (tiga) frasa utama sebagai narasi dominan yang dikembangkan. Ke-tiga (3) frasa itu seolah-olah menegasikan Indonesia membutuhkan; (1) “pemimpin (presiden) sederhana”; (2) pemimpin yang “merakyat” dan; (3) pemimpin yang berasal dari “wong cilik”. Dilihat dari ke tiga (3) frasa tersebut, tampak dengan jelas bahwa narasi pesan dan agenda politik kampanye pemilihan presiden hanya bertumpu pada sosok pemimpin (presiden) semata. Alih-alih memikirkan kebutuhan rakyat kecil dan bangsa, justru asik mengumbar dan memoles pesona, citra dan status sosok calon presiden dan wakilnya. Disini sosok figur calon menjadi ‘jualan’ politik tanpa gagasan cerdas dan solusi yang kongkrit.
Akibatnya hasil narasi mitos pilpres 2014 dan 2019 sulit dibuktikan kebenarannya dan relevansinya dengan kondisi masyarakat saat ini. Sebagai contoh, mitos kesederhanaan, kerakyatan dan rakyat kecil (wong cilik) seorang presiden, terbukti tidak mampu menyederhanakan atau menyelesaikan persoalan rakyat, bangsa dan negara. Rakyat kecil justru makin terpinggirkan dan tidak berdaya, ibarat pepatah lama ‘jauh panggang dari api’. Pada satu sisi, rakyat kecil masih berteriak lantang menuntut lapangan pekerjaan dan kesejahteraan mereka. Kita juga sering menyaksikan sebagian kelompok masyarakat dibungkam, digusur, diteror serta dibui dengan paket undang-undang ala oligarki (ITE, Omnibus low).
Tuduhan radikal dan teroris juga menghantui dan mengintai masyarakat yang mengemukakan pendapatnya. Disisi yang lain, negara dibuat melemah dan tidak berdaya, akibat perilaku elit penguasa mengobrak abrik kelembagaan negara, mulai dari DPR, KPK, hingga MK. Parahnya lagi, slogan “revolusi mental” dan nawacita sebagai tajuk visi, misi, dan program kerja yang dibanggakan berakhir menjadi ‘senjata makan tuan’, mengikis habis mental sebagian pejabat negara menjadi tidak bermoral dan beretika negarawan.
Metamorfosis Mitos Produk Dominasi dan Hegemoni Rezim
Kini, pada pemilihan presiden 2024, kemiripan mitos politik kembali muncul, dituding beririsan dan dikendalikan oleh kekuatan besar. Produktifitas mitos itu intens dan masif dipertontonkan diberbagai saluran media massa dan media sosial. Produksi dan konstruksi mitos tersebut terlihat dari susunan narasi, diksi, simbol atau slogan politik yang diusung, jauh dari gagasan cerdas. Keseluruhan argumentasi yang dibangun sulit ditemukan rujukan dan relevansinya, sebagaimana eksistensi mitos.
Jika pilpres 2014, 2019 narasi mitos muncul sebagai hasil diskursus publik terhadap persoalan kebangsaan yang mendesak. Maka pada pilpres 2024 narasi mitos merupakan hasil konstruksi wacana elit. Disini mitos mengalami pabrikasi dan komodifikasi dengan mengeksploitasi imaginasi masyarakat. Bahkan pabrikasi mitos menyasar dan beroperasi dalam pranata sosial, ekonomi dan komunitas masyarakat. Pada proses ini, wacana yang ingin dibentuk adalah dominasi dan hegemoni politik. Dominasi pada satu sisi bertujuan memaksakan pengaruh terhadap kelompok lain. Pada sisi yang lain hegemoni bertujuan menetapkan standar terhadap suatu nilai, norma, etik, termasuk informasi (pilpres) kepada setiap masyarakat (pemilih). Sehingga ukuran tentang benar-salah, baik-buruk, layak-tak layak, hingga loyal-kritis menjadi domain elit dan rezim politik (kekuasan).
Inilah yang disebut mitos menjadi instrumen politik sebagai jalan pintas menuju arah keseragaman dan keberlanjutan kekuasaan dalam rezim pilkada, pemilu dan pilpres. Pada konteks ini, mitos telah menjadi komoditi politik elit yang layak dijual ke publik. Melalui cara itu pula, mudah bagi elit politik menanamkan pengaruh dan standar yang ditentukan.
Mencermati anomali fenomena diatas, penulis merangkum beberapa indikasi pabrikasi mitos yang terbentuk dari praktik dominasi dan hegemoni yang telah dikondisikan. Pabrikasi mitos tersebut terdiri dari lima (5) frasa, yakni; (1) “pemimpin tegas; (2) pemimpin muda; (3) pemimpin eletis; (4) pemimpin gemoy; (5) politik riang gembira.
Jika dilihat dari ke lima (5) frasa tersebut cukup alasan mengatakan narasi pesan yang terkandung di dalamnya merupakan keberlanjutan dari tiga (3) frasa pada pemilihan presiden 2014 dan 2019. Kelima frasa tersebut hanyalah berganti kemasan, namun makna pesannya tetap merupakan kondisional elit. Sebagai contoh, mitos pilpres 2014 dan 2019, frasa ‘pemimpin sederhana’ berubah menjadi ‘pemimpin tegas’; frasa ‘pemimpin merakyat’ berubah menjadi ‘pemimpin muda’; frasa ‘pemimpin wong cilik’ berubah menjadi ‘pemimpin eletis. Hebatnya lagi, untuk tujuan menghindari polemik, kritik dan konflik terhadap persoalan politik, ekonomi, hukum dan kesejahteraan sosial, masa lalu dan masa kini, frasa ‘pemimpin gemoy’ dan ‘politik riang gembira’ sengaja disematkan dalam narasi mereka.
Hal ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan sosok pemimpin ideal yang selalu menggemaskan dan menyenangkan menghadapi persoalan kerakyatan, dan kebangsaan dalam segala suasana. Padahal persoalan carut marut negeri ini dalam berbagai aspek membutuhkan sosok pemimpin yang serius dan kritis. Mereka lupa, bahwa tidak semua masalah kerakyatan dan kebangsaan dapat diselesaikan dengan senyuman dan sukacita. Pemimpin gemoy dan politik riang gembira justru akan menumbuhkan kesadaran palsu dan pemilih irasional sebagian masyarakat. Sehingga tak mengherankan, saat ini muncul masyarakat yang dituntun oleh kesadaran palsu dan irasional bersuara lantang tentang ide ‘keseragaman’ dan narasi “keberlanjutan”. Hal ini sebagai bentuk dominasi dan hegemoni kepada pihak lain. Bahkan secara seragam produksi dan distribusi narasi “keberlanjutan” terus menerus digaungkan dalam berbagai situasi dan tempat yang tersedia maupun yang dipersiapkan. Apalagi jika cara tersebut didukung dan dikendalikan oleh kekuatan kelompok dominan yang memiliki relasi kekuasan, (partai politik dan rezim).
Pada konteks ini, kita dapat menduga ke-lima frasa yang disajikan, merupakan metamorfosis mitos pilpres 2014 dan 2019, sebagai strategi terselubung dari keberlanjutan rezim. Melalui strategi itu pula, narasi keberlanjutan dipergunakan sebagai alat membentengi, melindungi, dan menghindari pihak-pihak yang kritis atau berseberangan dengan isu sensitif baik persoalan politik, ekonomi, hukum maupun kesejahteraan sosial, masa lalu dan masa kini oleh rezim penguasa.
Sedangkan keseragaman dimaksudkan untuk menanamkan nilai dan informasi, termasuk mitos dalam menciptakan identitas masyarakat (pemilih) khususnya kaum milineal terhadap calon pemimpin ideal versi mereka. Untuk mencapai tujuannya, mereka menciptakan identitas pemilih ‘ekslusif’ (milineal-gen-z) melalui produk budaya populer yang tersedia saat ini. Bahkan untuk maksud tersebut, berbagai panggung, pentas atau forum milineal sengaja disiapkan bagi pemilih gen-z sekaligus karpet merah menyambut pesona sang figur calon presiden dan wakilnya.
Terlepas dari strategi capres diatas, hal sebaliknya berbeda ditingkat akar rumput. Beberapa kelompok masyarakat yang kritis dan menyuarakan narasi keberagaman dan perubahan, justru dituding tidak nasionalis, musuh pembangunan, bahkan anti pemerintah. Parahnya, beberapa aktivis pergerakan kampus dan civil society (Ketua BEM UI; BEM UGM) yang vokal membangun soliditas pemikiran dan kesadaran, perlahan mengalami persekusi,
Intimidasi dan Teror
Dengan kondisi seperti itu, lagi-lagi ini membuktikan kepada kita bahwa keunggulan dan pesona sosok figur calon presiden menjadi primadona dalam narasi, kampanye maupun debat politik. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa rezim penguasa yang memiliki relasi dengan calon presiden tertentu, dapat melakukan apapun, termasuk mengintai, mengawasi dan memata-matai aktifitas warga negaranya. Bahkan dalam keadaan tertentu, demi mencapai tujuannya rezim penguasa dapat merampas kebebasan individu warganya. Individu dibiarkan berjuang melawan praktik kesewenangan kekuasaan.
Tirani kekuasaan menjadi benteng menutupi kebobrokan dan ambisi aparatur kekuasaan. Situasi ini mirip dengan cerita film ‘enemy of the state’ dari Robert Dean. Dilain pihak, tindakan arogansi berlebihan dari rezim kekuasaan berupa pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat di depan umum, merupakan bentuk intervensi elit dan rezim terhadap pilihan politik masyarakat. Demikian pula sikap represif, persekusi, intimidasi, teror hingga pelaporan polisi terhadap para aktivis kampus dan kelompok civil society menunjukkan kepada kita, bahwa pilpres yang terhubung dengan rezim kekuasaan, sedang mempertontonkan apa yang dikenal dalam dunia jurnalistik sebagai serangan “kill the messenger”. Sebuah istilah yang akrab bagi para insan pers, media dan ilmuan komunikasi, yang menggambarkan tindakan pembunuhan karakter pembawa pesan, akibat produksi pesan yang tidak diinginkan.
Anomali Politik-Demokrasi dan Sikap Kita
Mencermati kondisi yang demikian, tidak berlebihan jika penulis menyebutnya sebagai anomali politik pilpres dan demokrasi yang selalu berulang dalam perhelatan politik negara demokrasi di dunia. Anomali politik ini dipaksa beroperasi pada wilayah kesadaran individu melalui mekanisme Alfred Schutz yakni internalisasi, eksternalisasi dan objektifikasi. Meminjam mekanisme tersebut, pemilih dipaksa menjadi bagian dari kelompok politik dominan, melakukan hegemoni terhadap pihak lain, sehingga membentuk atribut dan identitas gerakan bersama yang seragam.
Maka tidak heran, saat ini masif dijumpai gerakan bersama pabrikasi mitos menghiasi foto calon presiden dan wakilnya, dan caleg diberbagai tempat dan ruang publik. Narasi teks dan simbol mitos tersebut tertera mulai dari stiker, spanduk, banner baliho, media massa official, dan media sosial. Apa yang sedang terjadi saat ini menunjukkan secara nyata, bahwa pabrikasi mitos telah menggeser peradaban berpolitik serta realitas politik sesungguhnya. Pabrikasi mitos tersebut menjadi instrumen politik dan propaganda dalam memanipulasi dukungan dan partisipasi politik.
Dalam terminologi dan teori politik modern, hasil manipulasi realitas politik sangat bermanfaat dalam menanamkan pengaruh, dominasi dan hegemoni terhadap pihak lain. Sehingga peradaban berpolitik selalu terhubung dengan suatu rezim politik (kekuasaan). Meskipun terbuka peluang terjadinya benturan sosial terhadap warga negara. Dalam perspektif mikro politik negara berkembang, tesis Huntington, S, (2004) yang dikembangkan Ernesto, Hernadez dan Mazzuca (2021) mejelaskan hal ini. Bahwa praktik dominasi dan hegemoni suatu rezim kekuasaan melahirkan relasi kepentingan politik dengan suatu rezim politik berpotensi memunculkan benturan di tingkat warga negara. Sebagai bukti kongkrit, keributan dan pertengkaran yang terjadi pada forum debat ke 2 pilpres yang melibatkan pendukung 2 calon presiden (Prabowo vs Ganjar P), memperkuat tesis Huntington nyata terjadi. Pada batas ini, mungkin kita bisa bersepakat atau tidak, bahwa proses atau hasil pemilihan presiden tahun 2024, akan berpotensi konflik di tingkat warga negara. Konflik yang disebabkan oleh narasi mitos dan tindakan irasional sesama pendukung. Sementara janji-janji politik presiden terpilih diyakini tapi sulit ditunaikan, apalagi dibuktikan dalam kinerja pemerintahannya. Hal inilah yang disebut sebagai sebuah fenomena anomali demokrasi yang selalu berulang dalam perhelatan politik seluruh negara-negara di dunia.
Peristiwa demi peristiwa diatas menunjukkan kepada kita semua sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk tidak terbuai, dan tidak terhasut oleh produksi dan pabrikasi mitos politik yang semu. Demikian pula sikap glorifikasi terhadap status, pesona, citra dan prestasi figur seorang pemimpin tidak pantas dilakukan. Diperlukan nalar kritis mencerna dan menolak setiap praktik-praktik politik yang irasional. Menurut hemat penulis, potret demokrasi yang tersaji di ruang publik saat ini, adalah sebuah kemunduran demokrasi sekaligus kegagalan rekruitmen (kepemimpinan) politik. Sungguh sebuah ironi dan tantangan besar bagi bangsa Indonesia yang notabene menganut sistem demokrasi terbesar di dunia.
Bacaan:
1.Endibiaro, 2014; Meta Komunikasi Jokowi Terkini: https://www.kompasiana.com/
2.Bastian dan Mitchell; https://www.amazon.com.(23.00/27 Nop/2023)
3. Hoed.,B. H, 2014; Semiotic: Dinamika Sosial dan Budaya.
4. Huntington, S.P, 2004; Benturan antar Peradaban: Masa depan Politik Dunia; Yayasan Qalam.
5. Ernesto Dalbo, Pablo Hernandez, Sebastian Mazzuca, 2021 Paradox-of-civilization-preinstitutional-sources; https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review, Vol.116- Ed.1
[ad_2]
Source link